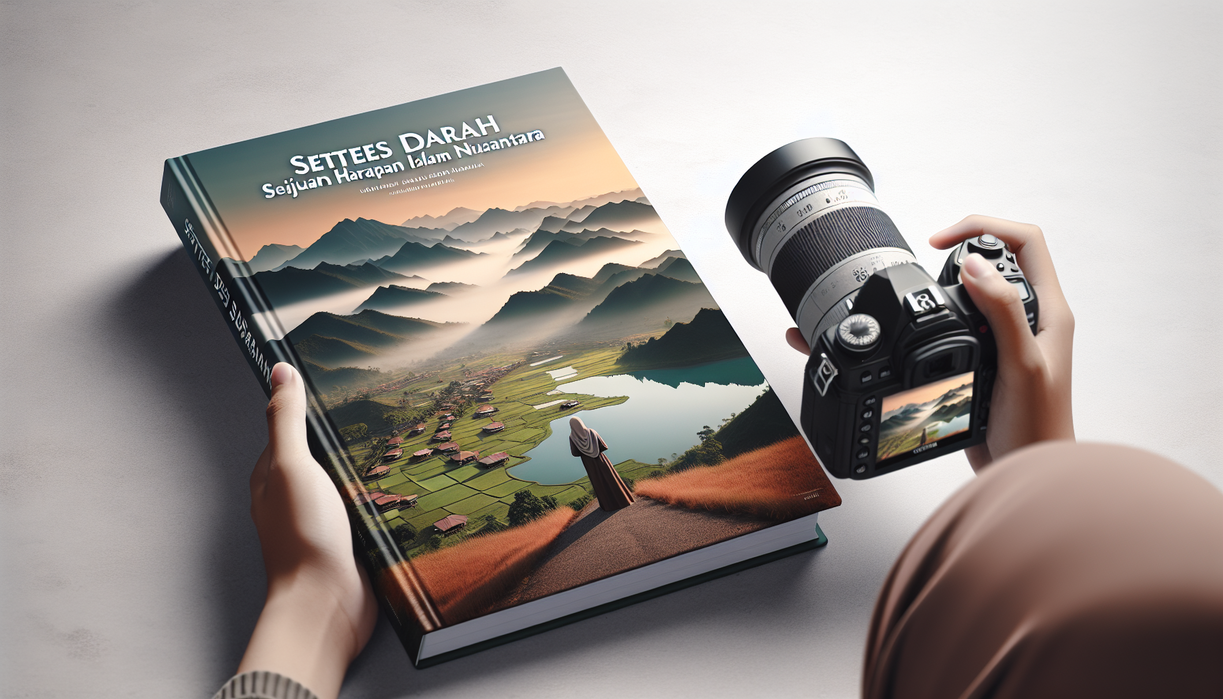thenewartfest.com – Podcast Richard Lee kembali jadi buah bibir. Bukan sekadar karena tamu populer, melainkan karena cerita kelam yang diungkap seorang perempuan muda soal dugaan kekerasan seksual oleh ustaz terkenal jebolan televisi. Pengakuan tersebut muncul dalam suasana obrolan santai, khas podcast Richard Lee, namun isinya berat, sensitif, serta memicu emosi publik.
Kisah itu langsung menyebar luas, memantik pro dan kontra di ruang digital. Alih-alih empati, sebagian netizen justru menyalahkan korban. Komentar seperti “itu mah mau” berseliweran, memperlihatkan betapa dangkalnya pemahaman banyak orang terkait relasi kuasa, persetujuan, juga trauma. Di titik inilah, podcast Richard Lee tidak lagi sekadar hiburan, melainkan cermin cara kita memandang korban kekerasan seksual.
Podcast Richard Lee dan Ruang Curhat yang Berisiko
Format podcast Richard Lee dikenal ringan, cair, serta dekat dengan gaya ngobrol sehari-hari. Tamu undangan bebas bercerita, termasuk sisi gelap hidup yang jarang mereka ungkap di ruang lain. Kekuatan format ini terletak pada rasa aman yang tercipta, seakan kamera tidak ada. Namun, ketika cerita menyentuh isu sensitif seperti kekerasan seksual, suasananya berubah total. Setiap kalimat berpotensi menyalakan kontroversi, baik ke arah empati maupun serangan.
Dalam episode yang ramai dibicarakan, seorang perempuan mengaku diperkosa ustaz jebolan TV di hotel hingga tiga kali. Cerita tersebut disampaikan cukup detail, membuat penonton merasa seolah berada di ruangan sama. Reaksi emosional pun meledak. Banyak yang langsung percaya, banyak juga yang ragu, bahkan menertawakan. Disinilah tantangan besar ekosistem podcast Richard Lee: bagaimana menjaga ruang curhat tetap manusiawi, sekaligus bertanggung jawab secara etis.
Podcast bukan pengadilan, namun jangkauannya sangat luas. Ketika tuduhan serius terucap, reputasi seseorang bisa runtuh hanya lewat satu klip pendek. Di sisi lain, bagi korban, berbicara di ruang publik kadang menjadi jalan terakhir untuk didengar. Podcast Richard Lee berada tepat di persimpangan itu: antara memberi panggung bagi suara korban dan risiko trial by social media. Garisnya tipis, sering kali kabur.
Netizen, Victim Blaming, dan Mentalitas Menyalahkan Korban
Salah satu hal paling mengganggu dari respons publik ialah maraknya victim blaming. Alih-alih bertanya apakah korban mendapat keadilan, banyak yang justru sibuk menilai pakaian, gestur, atau keputusan personal korban. Komentar “itu mah mau” mencerminkan budaya yang masih menganggap seks hanya soal keinginan dua pihak, tanpa memeriksa konteks tekanan, ancaman, atau ketimpangan kekuasaan. Di sini, narasi media sosial menjadi pisau bermata dua.
Ustaz jebolan TV tentu punya posisi sosial kuat. Popularitas, citra religius, serta pengaruh publik membentuk relasi kuasa timpang dengan perempuan awam. Saat korban mengaku dilecehkan oleh figur selevel itu, wajar bila muncul rasa takut, bingung, bahkan lumpuh. Banyak orang bertanya, “Kenapa tidak langsung kabur?” tanpa memahami bahwa otak manusia dapat membeku saat menghadapi ancaman, fenomena yang dikenal sebagai freeze response. Namun nuansa ini sering hilang di kolom komentar.
Dari sisi pribadi, saya melihat fenomena ini sebagai cermin minimnya literasi seksualitas dan psikologi trauma di Indonesia. Podcast Richard Lee, meski bukan program edukasi formal, justru memperlihatkan kekosongan tersebut. Setiap kali korban bicara, banjir komentar menghina muncul. Reaksi itu menunjukkan bahwa pekerjaan rumah kita bukan hanya menuntut kebenaran kasus, tapi juga membenahi cara berpikir kolektif yang terlalu cepat menghakimi korban.
Etika Konten, Tanggung Jawab Kreator, dan Harapan ke Depan
Kasus pengakuan kekerasan seksual di podcast Richard Lee mestinya jadi momen refleksi, bukan sekadar drama musiman. Kreator konten perlu memikirkan protokol saat tamu membawa tuduhan serius: apakah sudah ada pendampingan hukum, apakah korban paham konsekuensi publik, juga apakah narasi diedit cukup sensitif. Di sisi lain, penonton perlu belajar menahan diri, berhenti menyalahkan korban, serta mulai mempertanyakan sistem yang membuat pelaku sering lolos. Ruang digital bisa tetap jadi tempat curhat berani, asalkan kita menggabungkan empati, skeptisisme sehat, serta komitmen pada keadilan. Akhirnya, tujuan tertinggi konten sekuat podcast Richard Lee seharusnya bukan cuma viral, melainkan membantu membangun budaya yang lebih peduli pada keselamatan, martabat, dan suara korban.